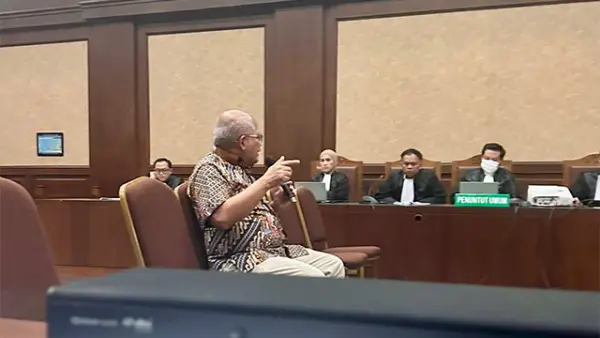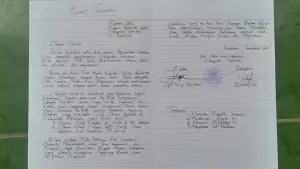SUKABUMIUPDATE.com - Indonesia telah kehilangan peluang emas memerangi Covid-19 di masa awal pandemi. Saat ini, kita dan sejumlah negara lain di dunia menggantungkan diri pada vaksin. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di negeri ini yang menerima suntikan "penangkal" Virus Corona tersebut. Tak sendiri, pada Rabu, 13 Januari 2021, Jokowi disuntik di Istana Merdeka Jakarta bersama beberapa tokoh lainnya, termasuk artis sekaligus influencer Raffi Ahmad.
Suntikan yang diterima Jokowi menjadi tanda dimulainya program vaksinasi Covid-19 gelombang pertama di Indonesia. Berdasarkan rencana nasional, ada sekitar 181,5 juta orang yang ditargetkan menerima vaksin dengan total kebutuhan mencapai 426,8 juta dosis.
Pemerintah bahkan optimis dapat menyelesaikan program ini dalam rentang waktu 15 bulan, yakni sejak Januari 2021 hingga Maret 2022. Jumlah 181,5 juta orang tersebut setara dengan kurang lebih 70 persen populasi. Dengan demikian, program ini diharapkan bisa memicu kekebalan kelompok atau herd immunity.
Disebutkan pula ada 13.000 puskesmas, dengan hampir 2.500 rumah sakit, serta didukung dengan 49 kantor kesehatan pelabuhan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk program vaksinasi tersebut, lengkap dengan 30.000 vaksinator yang dikerahkan pemerintah. Sementara ini tercatat ada 3 juta dosis vaksin dari Sinovac Biotech yang telah diterima Indonesia.
Meskipun demikian, masyarakat harus tetap menyadari bahwa vaksin tidak menjadi jaminan utama dapat mengatasi Pandemi Covid-19 dengan seketika.
Diakui atau tidak, kunci emas untuk mengatasi penyebaran Virus Corona ini justru pada penerapan protokol kesehatan alias prokes yang disiplin.
Nyaris semua orang telah mengetahui 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Tetapi penerapannya masih nisbi dan belum konsisten. Begitu pula dengan penerapan 4T, yakni tracing, tracking, testing, dan treatment.
Pemerintah Indonesia terkesan bersandar penuh pada "kemanjuran" vaksin. Belum terlihat adanya langkah pengetatan protokol kesehatan yang efektif dan konsisten atau langkah penanggulangan yang lain untuk mengatasi pandemi ini.
Belum lagi persoalan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah penolakan masyarakat terhadap program vaksinasi tersebut.
Project Integration Manager of Research and Development Division PT Bio Farma, Neni Nurainy mengatakan, dalam survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan, WHO, dan UNICEF pada September tahun lalu, 7,60 persen masyarakat di Indonesia tidak mau divaksin. Meskipun sebanyak 64,81 persen masyarakat lainnya menjawab setuju divaksinasi. Selain itu, ada pula 27,60 persen masyarakat yang belum tahu divaksin atau tidak.
Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa meyakinkan masyarakat agar mau mengikuti program vaksinasi Covid-19 tersebut. Namun langkah awal pemerintah yang melibatkan influencer dalam vaksinasi perdana, sempat menuai sorotan karena yang bersangkutan justru berkumpul tanpa memakai masker dan menjaga jarak usai mendapat suntikan, bersamaan dengan Jokowi.
Apakah Vaksin Ampuh Atasi Pandemi?
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sendiri sudah mengumumkan bahwa efikasi vaksin Sinovac Biotech yang diuji klinis di Indonesia hanya sebesar 65,3 persen. Angka ini lebih rendah ketimbang efikasi vaksin Sinovac yang diuji di Turki dan Brasil. Masing-masing dari dua negara itu telah lebih dulu mengumumkan klaim efikasi yang dihasilkan sebesar 91,2 persen dan 78,0 persen.
Efikasi sendiri merupakan persentase penurunan suatu penyakit pada sekelompok orang yang menerima vaksinasi dalam uji klinis. Hal ini berbeda dari efektivitas vaksin Covid-19, dimana mengukur seberapa baik vaksin bekerja saat diberikan kepada orang-orang di komunitas di luar uji klinis.
Ihwal perbedaan efikasi sesama hasil uji klinis vaksin Sinovac tersebut, Tim Komnas Penilai Obat menyebut, ada beberapa faktor yang dimungkinkan menjadi penyebabnya. Antara lain kondisi epidemiologi Covid-19 di Indonesia, perilaku masyarakat, dan karakteristik populasi atau subjek yang dilibatkan dalam penelitian.
Melansir dari Tirto, Profesor Sosiologi Bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir mengatakan, pandemi terjadi saat patogen (agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya) berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Dengan kata lain, selama masih ada masyarakat yang dapat terjangkit, maka selama itu pula pandemi tidak akan selesai.
Ia memberikan contoh pada wabah sebelumnya, yakni SARS-CoV (2002-2003) dan MERS-CoV (2012). Kedua wabah tersebut berhasil diatasi tanpa vaksin, namun dengan tindakan preventif. Lalu flu Spanyol pada tahun 1918 yang muncul dalam sejumlah gelombang hingga akhirnya menghilang.
Pada intinya, Sulfikar menegaskan bahwa pandemi tidak akan pernah hilang bila respon sosial lemah. Paling bagus hanya akan berkurang sedikit, lalu naik kembali dan seterusnya. Hingga tersisa sedikit orang yang belum terinfeksi, kemudian penularan berkurang dan pandemi berakhir.
"Jika Flu Spanyol dikalahkan dengan intervensi sosial. Maka Covid-19 kemungkinan besar dikalahkan intervensi medis, yaitu vaksin," ucap Sulfikar.
Namun pertanyaan mendasar muncul, apakah protokol kesehatan tidak dibutuhkan lagi bila telah menerima vaksin?
Tak sedikit orang yang menganggap bahwa vaksin merupakan obat kebal super. Padahal, vaksin tidak seratus persen menjamin tubuh terlindungi dari serangan virus.
Mesti diingat bahwa sekalipun telah menjalani vaksinasi, tubuh seseorang tetap memerlukan waktu untuk membentuk imunitas. Dari sejumlah fase uji klinis, perlu dua kali injeksi vaksin Sinovac dalam rentang 14 hari agar seseorang imun terhadap Virus Corona. Belum lagi antibodi yang baru terbentuk maksimal tiga bulan pasca injeksi kedua.
Artinya, seseorang yang baru saja divaksinasi pun tetap memiliki kemungkinan terinfeksi Virus Corona ketika kekebalannya belum terbentuk.
Belajar dari Ebola di Kongo
Wabah Ebola di Kongo setidaknya dapat menjadi gambaran bagaimana vaksinasi dapat gagal akibat melalaikan penerapan protokol kesehatan.
Kasus pertama Virus Ebola ditemukan pada tahun 1976 di Republik Demokratik Kongo. Namun pada tahun 2014, wabah tersebut merenggut korban jiwa lebih dari 11 ribu orang dan menginfeksi lebih dari 28 ribu warga. Guinea, Liberia, dan Sierra Leone merupakan negara-negara yang mengalami dampak wabah terparah.
Gelombang kedua wabah tersebut terjadi di dua provinsi di Kongo pada tahun 2018, yakni Kivu Utara dan Ituri. Diketahui ada lebih dari 2.500 warga terinfeksi Virus Ebola dan dua pertiganya meninggal dunia. Kala itu, produksi vaksin Virus Ebola dipercepat dan disalurkan dengan syarat kedaruratan, nyaris sama seperti vaksin Covid-19 saat ini.
Pembuatan vaksin Ebola darurat saat itu menghabiskan waktu lima tahun, dari 2014-2019. Hal itu terbilang lebih cepat ketimbang proses pengembangan dan persetujuan vaksin di masa normal yang biasanya memerlukan waktu 10-15 tahun.
Kemudian pada periode 2018-2020, ada lebih dari 300 ribu orang yang divaksinasi. Tetapi, wabah Ebola tetap ada pada tahun 2018 dan yang terbaru pada Juni 2020 lalu.
Lalu mengapa wabah Ebola tetap muncul meskipun telah ada vaksin? Sejumlah faktor disinyalir menjadi penyebabnya, antara lain konflik yang terjadi di Kongo.
Tak hanya itu, sejarah panjang kekerasan juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan asing dan mengakibatkan sekitar sepertiga dari seluruh kematian terjadi di masyarakat umum tinggal, bukan di pusat perawatan Ebola. Dengan kata lain, mereka tidak mencari pengobatan dan berisiko menyebarkan penyakit ke tetangga dan kerabat terdekat.
Melansir dari laporan BBC, dalam rentang Januari hingga Juli 2019, terjadi 198 serangan terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas perawatan Ebola yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 58 lainnya cedera.
Dalam kondisi semacam itu, tentu sangat sulit untuk menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan Virus Ebola. Ada pula masyarakat Kongo yang beranggapan bahwa wabah tersebut hanya isu yang sengaja disebar sebagai dalih eksploitasi. Hal itu berkaitan dengan sejarah kolonialisme Eropa yang pernah mencengkeram wilayah tersebut.
Fenomena seperti itu persis dengan sebagian masyarakat Indonesia yang menyebut bahwa Covid-19 adalah konspirasi. Ada juga kalangan "antivaksin" yang menyampaikan teori-teori irasional, mulai dari vaksin berisi chips, komposisi vaksin yang bermasalah dan justru berbahaya, hingga menyangkut halal-haram zat penyusunnya.
Membenahi penerimaan dan kepercayaan publik sekarang ini memang bukan perkara gampang. Terlebih kegagalan pemerintah dalam mengatasi pandemi selama 10 bulan ini sudah lebih dulu membuat keyakinan masyarakat merosot. Belum lagi soal persoalan data yang dinilai tidak pernah dibuka secara transparan.
Sumber: Tirto | BBC | Tempo






![Prediksi Konser PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] di Jakarta Hari Ini (Sumber : Instagram/@plave_official)](https://media.sukabumiupdate.com/media/2025/10/18/1760770262_68f338d6053df_KxQwzU7TCFyWmhJ6TxJx-medium.webp)